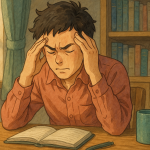Setiap pagi, Arif membuka matanya dengan refleks meraih ponsel. Belum sempat duduk, ia sudah membaca notifikasi email kantor, pesan WhatsApp dari grup keluarga, dan satu komentar pedas di media sosial. Sebelum sarapan, pikirannya sudah penuh. Sore harinya, saat sedang menyelesaikan laporan mingguan, notifikasi dari empat aplikasi berbeda saling berlomba memanggil perhatiannya. Ia merasa sibuk, tapi tak kunjung produktif. Kepalanya berat, dadanya sesak, dan tidurnya pun terganggu.
Fenomena ini tidak hanya dialami Arif. Banyak orang merasakan hal serupa. Di tengah segala kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan teknologi digital, tekanan mental justru meningkat. Data dari World Health Organization menunjukkan lonjakan kasus gangguan kecemasan dan stres sejak penggunaan internet dan media sosial meluas secara global. Di Indonesia, survei oleh Kementerian Kesehatan dan beberapa universitas menemukan bahwa lebih dari 60 persen generasi muda mengaku mengalami stres yang berkaitan dengan penggunaan gawai, ekspektasi pekerjaan, dan tekanan sosial daring.
Era digital mempercepat segalanya. Informasi datang deras tanpa henti. Kita bisa bekerja dari mana saja, tapi juga bisa dibebani pekerjaan kapan saja. Batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur. Media sosial, yang awalnya menjadi sarana ekspresi dan koneksi, kini juga menjadi sumber tekanan. Perbandingan hidup, ekspektasi pencapaian, validasi dari jumlah likes, semuanya menyusup dalam bawah sadar. Tak heran jika banyak orang merasa lelah meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.
Stres, secara ilmiah, adalah respons tubuh terhadap ancaman atau tekanan. Dalam kadar tertentu, stres bermanfaat karena mendorong kewaspadaan dan kesiapan menghadapi tantangan. Namun jika berlangsung lama atau datang bertubi-tubi tanpa kendali, stres menjadi kronis dan merusak. Hormon kortisol yang terus-menerus dilepaskan ke aliran darah dapat melemahkan sistem imun, mengganggu tidur, memengaruhi metabolisme, bahkan mempercepat penuaan sel. Otak pun terpengaruh, terutama pada bagian hippocampus yang bertugas mengatur ingatan dan emosi.
Dalam konteks digital, para ilmuwan memperkenalkan istilah techno-stress. Ini adalah tekanan mental yang muncul akibat penggunaan teknologi secara berlebihan atau tidak seimbang. Bentuknya bisa beragam, mulai dari kelelahan digital, kecemasan jika tidak memegang ponsel, sulit fokus karena multitasking, hingga gangguan tidur akibat paparan cahaya biru di malam hari. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa terlalu banyak berpindah tugas secara digital (switching task) memperburuk memori jangka pendek dan meningkatkan rasa tertekan. Otak manusia tidak dirancang untuk terus-menerus berpindah perhatian setiap beberapa detik.
Namun sains tidak hanya memotret masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Salah satu pendekatan yang banyak diteliti adalah mindfulness. Praktik ini mengajak kita untuk menyadari apa yang sedang dirasakan saat ini, tanpa menghakimi. Studi dari Harvard Medical School menemukan bahwa mindfulness selama delapan minggu dapat menurunkan tingkat kortisol dan meningkatkan aktivitas area otak yang berperan dalam pengendalian emosi. Latihan sederhana seperti menarik napas dalam-dalam selama lima menit tanpa gangguan, atau memperhatikan suara alam tanpa membuka ponsel, terbukti menenangkan sistem saraf otonom.
Strategi lain adalah digital detox, yaitu jeda dari semua bentuk perangkat digital untuk sementara waktu. Penelitian dari University of Bath menunjukkan bahwa peserta yang menjalani digital detox selama tiga hari mengalami peningkatan kualitas tidur, suasana hati, dan konsentrasi. Namun detox tidak selalu harus ekstrem. Bahkan mengatur waktu layar (screen time) dengan batas harian, mematikan notifikasi yang tidak perlu, atau menggunakan fitur fokus di ponsel dapat memberikan dampak yang signifikan.
Penting juga untuk menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Membuat jadwal kerja yang terstruktur, menetapkan waktu tanpa layar di malam hari, dan menciptakan rutinitas offline seperti membaca buku fisik atau berjalan kaki di alam, semuanya membantu mengurangi tekanan digital. Beberapa perusahaan bahkan mulai menerapkan kebijakan “no email after hours” demi menjaga kesehatan mental karyawan. Ini bukan kemunduran, tetapi penyesuaian terhadap fakta bahwa otak manusia butuh jeda.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, memulai pagi tanpa langsung membuka ponsel. Menetapkan waktu offline satu jam sebelum tidur. Menghindari media sosial saat makan. Menggunakan aplikasi pelacak waktu layar untuk memahami kebiasaan digital kita. Menyadari kapan tubuh memberi sinyal lelah, lalu menanggapi dengan istirahat sejenak, bukan dengan menggulir layar lebih jauh.
Arif akhirnya memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Ia kini menyalakan mode senyap di ponselnya setelah jam delapan malam. Ia tidak lagi membuka email kantor saat akhir pekan. Ia memulai hari dengan lima menit napas sadar di balkon, dan mengganti waktu media sosial dengan membaca buku. Ia mengaku lebih tenang, lebih fokus, dan tidak lagi mudah tersinggung. Perubahan kecil ini membuatnya merasa kembali menjadi manusia, bukan sekadar pengguna.
Di era digital ini, teknologi bukanlah musuh. Justru ia bisa menjadi alat bantu yang luar biasa, jika digunakan dengan sadar. Namun kita tetap harus menjadi pengendalinya, bukan sebaliknya. Karena tubuh dan pikiran kita tetap hidup dalam ritme biologis yang butuh ketenangan, bukan sekadar kecepatan. Mengelola stres di era digital bukan berarti menolak teknologi, melainkan belajar menavigasinya dengan lebih bijak. Itulah yang kini sedang dibuktikan oleh sains, dan bisa kita mulai dari langkah sederhana hari ini.
Discover more from drBagus.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.